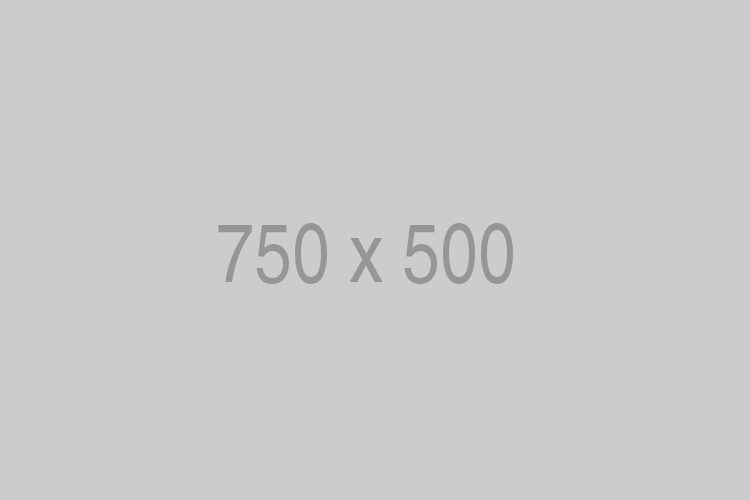MK Bak ‘Anak Macan’ yang Menggigit Induknya (DPR/MPR) Sendiri? Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Solusi Reformasi atau Masalah Baru?

KEPUTUSAN MK ini berpotensi melewati batas peran lembaga yudikatif dalam sistem trias politica
Oleh : Sugiyanto (SGY)
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)
Sesungguhnya, saya enggan menulis artikel ini karena sejak awal telah melihat potensi polemik besar yang mungkin timbul dari masalah ini. Namun, karena pro dan kontra terus berkembang, saya akhirnya memutuskan untuk menuliskannya. Tujuannya adalah untuk memberikan sudut pandang lain, yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Sebagaimana diketahui, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 26 Juni 2025 telah mengubah peta ketatanegaraan Indonesia secara signifikan. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus diselenggarakan secara terpisah, dengan rentang waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua setengah tahun.
Dengan demikian, pemilu nasional (untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD) tidak lagi dilangsungkan secara bersamaan dengan pemilu lokal (untuk memilih DPRD, gubernur, bupati/wali kota). Putusan ini sekaligus menandai berakhirnya skema “Pemilu Lima Kotak” yang selama ini menjadi ciri khas sistem pemilu serentak nasional sejak 2019.
Secara sepintas, putusan ini mungkin terlihat sebagai langkah reformasi pemilu yang bertujuan meningkatkan efektivitas, mengurangi kompleksitas teknis, dan memperbaiki kualitas demokrasi. Namun di balik itu, tersembunyi sejumlah persoalan serius yang tidak hanya mengganggu stabilitas sistem hukum dan politik nasional, tetapi juga berpotensi melanggar konstitusi secara substantif. Setidaknya terdapat lima alasan utama yang menjadi dasar permasalahan dalam putusan MK ini.
Pertama, dari segi kewenangan, keputusan MK ini berpotensi melewati batas peran lembaga yudikatif dalam sistem trias politica. Penentuan desain dan jadwal pemilu merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi domain pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah.
Dengan mengambil alih peran tersebut, MK seolah bertindak sebagai legislator negatif yang berubah menjadi legislator positif. Ia tidak hanya membatalkan norma hukum, tetapi juga memaksakan model kebijakan tertentu tanpa proses politik terbuka dan deliberatif. Ini merupakan preseden yang berbahaya dan menunjukkan kecenderungan aktivisme yudisial yang terlalu agresif.
Kedua, putusan ini menciptakan kerancuan konstitusional terkait status DPRD dalam skema pemilu. Pasal 22E UUD 1945 secara eksplisit menyebut bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Artinya, pemilu DPRD secara konstitusional merupakan bagian integral dari pemilu nasional, bukan bagian terpisah yang bisa dijadwalkan tersendiri.
Dengan memisahkan pemilu DPRD dari pemilu nasional, Putusan MK secara tidak langsung menciptakan kategori baru yang tidak dikenal dalam konstitusi. Dalam konstitusi, tidak terdapat istilah “pemilu daerah” atau “pemilu lokal”. Pemilu hanya dikenal sebagai satu kesatuan untuk memilih DPR, DPD, Presiden, dan DPRD.
Lebih dari itu, pemisahan ini berisiko menyebabkan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Risiko tersebut muncul karena pelaksanaan Pemilu DPRD pada tahun 2029 berpotensi berlangsung di luar siklus lima tahunan. Jika hal ini terjadi, maka jelas bertentangan dengan prinsip periodisasi pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
Jika masa jabatan DPRD diperpanjang demi menyesuaikan jadwal baru yang terpisah dari pemilu nasional, maka itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap konstitusi. Bahkan, ini dapat dianggap sebagai bentuk konstitusionalisasi jabatan tanpa mandat rakyat—sebuah bentuk perampasan kedaulatan rakyat secara hukum.
Ketiga, status hukum Pilkada kembali menjadi ambigu. Sejak 2009, Pilkada ditempatkan dalam rezim pemilu, dan sengketanya diselesaikan oleh MK. Namun, jika Pilkada tidak lagi dianggap bagian dari pemilu nasional sebagaimana dimaknai dalam putusan ini, maka muncul peluang dikembalikannya kewenangan sengketa Pilkada ke Mahkamah Agung, sebagaimana sebelum tahun 2009.
Dengan begitu, tentu hal tersebut tidak hanya membuka kembali diskursus lama, tapi juga berpotensi menurunkan kualitas penyelesaian sengketa. Selain itu hal ini juga berpotensi menciptakan dualisme yurisdiksi yang membingungkan serta inkonsisten.
Keempat, konsekuensi praktis dari pemisahan pemilu sangat kompleks dan bisa membebani negara. Pemilu terpisah berarti penyelenggaraan dua kali tahapan, dua kali anggaran, dua kali mobilisasi aparat keamanan dan logistik, serta dua kali potensi kerawanan politik dan konflik sosial.
Jeda waktu dua hingga dua setengah tahun berisiko menciptakan fragmentasi legitimasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, hal ini juga akan memperpanjang masa jabatan kepala daerah non-definitif atau pejabat (Pj), serta mengacaukan kesinambungan pembangunan di daerah. Semua ini justru bertolak belakang dengan tujuan konsolidasi demokrasi dan efisiensi sistem pemilu yang sebelumnya diupayakan melalui pelaksanaan pemilu serentak.
Keterpaksaan publik untuk menerima keberadaan pejabat (Pj) kepala daerah demi terselenggaranya Pilkada Serentak 2024 merupakan bentuk pengorbanan besar dalam demokrasi. Jelas, hal ini merupakan luka demokrasi yang semestinya tidak perlu terulang. Bagaimana mungkin, pada saat rakyat seharusnya menggunakan hak demokrasinya untuk memilih kepala daerah secara langsung, justru hak itu dirampas oleh aturan non-demokratis melalui penunjukan pejabat (Pj)? Ini adalah preseden yang seharusnya tidak dibiarkan terjadi lagi.
Kelima, terdapat kecurigaan politik atas dugaan adanya aktor dan motif di balik putusan ini. Argumentasi atas dukungan pada putusan MK tersebut memang membawa narasi akademik dan normatif tentang perbaikan kualitas demokrasi. Namun, saya menduga, bahwa mungkin saja desakan atas pemisahan pemilu ini justru berasal dari kekuatan politik tertentu yang merasa diuntungkan jika daerah tidak lagi langsung terhubung dengan siklus politik nasional.
Dalam skenario penundaan dua hingga dua setengah tahun bagi jabatan kepala daerah yang tidak sejalan dengan siklus pemilu nasional, terdapat potensi besar bagi partai dominan untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Melalui perpanjangan masa jabatan penjabat (Pj) kepala daerah, posisi strategis ini dapat diisi tanpa melibatkan partisipasi rakyat. Dengan kata lain, rakyat disingkirkan dari ruang kontrol langsung terhadap pemerintahan lokal.
Secara filosofis, Putusan MK ini mencerminkan ketegangan antara dua arus besar dalam demokrasi. Pertama, demokrasi prosedural yang berlandaskan pada aturan hukum. Kedua, demokrasi substantif yang menekankan keadilan dan partisipasi rakyat.
Namun, dalam kasus Putusan MK tersebut, justru muncul potensi penyimpangan dari kedua prinsip demokrasi tersebut. Ada kemungkinan besar rakyat tidak lagi memiliki ruang kontrol lima tahunan terhadap DPRD mereka. Selain itu, terdapat potensi bahwa aturan hukum (konstitusi) justru dilenturkan demi alasan “efektivitas” yang belum terbukti secara empiris.
UUD 1945 hasil amandemen jelas dan tegas dalam menentukan sistem pemilu. Pasal 22E UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD.
Tidak ada ruang bagi tafsir alternatif yang memisahkan pemilu DPRD sebagai pemilu daerah. Penempatan Pilkada dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah bukan berarti bahwa Pilkada bukan bagian dari pemilu, tetapi lebih karena Pilkada merupakan mekanisme demokrasi lokal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal 22E.
Secara normatif, putusan ini membuka ruang bagi pembajakan konstitusi melalui tafsir sepihak oleh lembaga yudikatif. Mahkamah Konstitusi (MK), yang seharusnya berperan sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution), justru telah melampaui kewenangannya. Dalam kondisi ini, bisa muncul anggapan bahwa MK seolah menjadi “anak macan” yang menggigit induknya sendiri, yakni DPR dan MPR—lembaga-lembaga yang notabene telah melahirkan MK melalui proses panjang Amandemen UUD 1945.
Jika tafsir konstitusi dapat dilenturkan sedemikian rupa demi mendukung kebijakan yang tidak lahir dari proses demokratis, maka kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang netral patut dipertanyakan. Pandangan lain yang mungkin muncul adalah: jika selama ini MK dianggap sebagai satu-satunya garda penjaga konstitusi, lalu siapa yang akan menjaga konstitusi jika MK sendiri yang melanggarnya?
Terkait semua uraian tersebut diatas, rakyat perlu menyadari bahwa putusan MK tersebut bukan hanya menyangkut soal teknis pemilu, tapi menyangkut hak dasar mereka untuk memilih wakil-wakilnya secara reguler dan dalam sistem yang adil. Penundaan pemilu DPRD, perpanjangan jabatan Pj kepala daerah, serta pemisahan antara pemilu nasional dan lokal adalah kombinasi berbahaya yang dapat melumpuhkan kontrol demokratis rakyat terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, putusan MK tersebut boleh jadi lebih tepat disebut sebagai masalah baru, bukan solusi.
Memang benar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta wajib dijalankan oleh semua pihak. Tidak melaksanakan putusan MK merupakan tindakan yang melanggar hukum dan konstitusi. Di sisi lain, melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 juga berpotensi menabrak konstitusi itu sendiri. Situasi ini menyerupai buah simalakama.
Dalam konteks tersebut, peran masyarakat sipil, kalangan akademisi, organisasi kepemiluan, dan partai politik menjadi sangat penting. Bagi semua pihak yang berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi, isu ini perlu dibahas secara serius dan mendalam. Situasi ini jelas menempatkan DPR, pemerintah, dan pihak-pihak terkait dalam posisi sulit—bagai buah simalakama—namun tetap harus diambil sebuah keputusan.
Jika dipandang perlu, DPR dan pihak-pihak terkait dapat mendorong revisi konstitusi melalui jalur legislatif atau mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagai respons atas putusan tersebut. Jika hal ini diabaikan, masa depan demokrasi Indonesia akan semakin ditentukan oleh tafsir hukum yang berpihak, bukan oleh kehendak rakyat yang berdaulat.
Memang, terdapat maksud baik di balik putusan MK tersebut, yang mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam sistem hukum pemilu dan ketatanegaraan kita. Namun, perbaikan semestinya dilakukan secara bertahap dan sistematis—bukan melalui keputusan yang justru menimbulkan polemik besar, seperti yang tercermin dalam putusan ini. Situasi ini tentu menjadi persoalan serius bagi DPR, pemerintah, dan semua pihak yang peduli terhadap masa depan demokrasi di negeri ini.