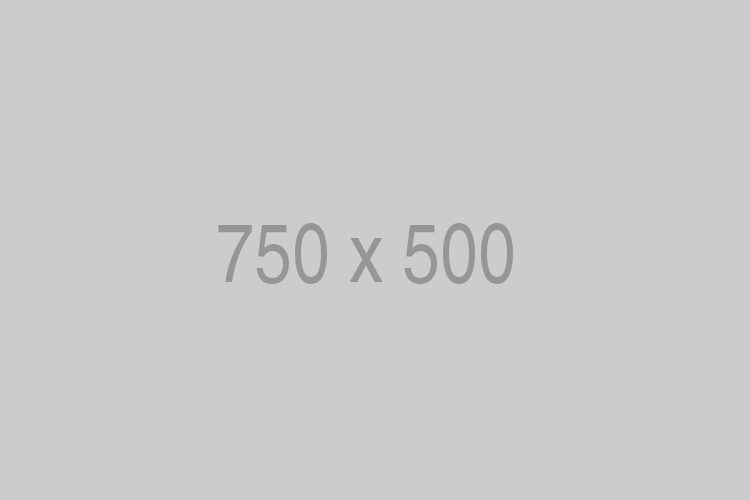DPR Tak Bisa Lagi Dibubarkan: Kecuali dengan Cara Non-Konstitusional, “Revolusi?”
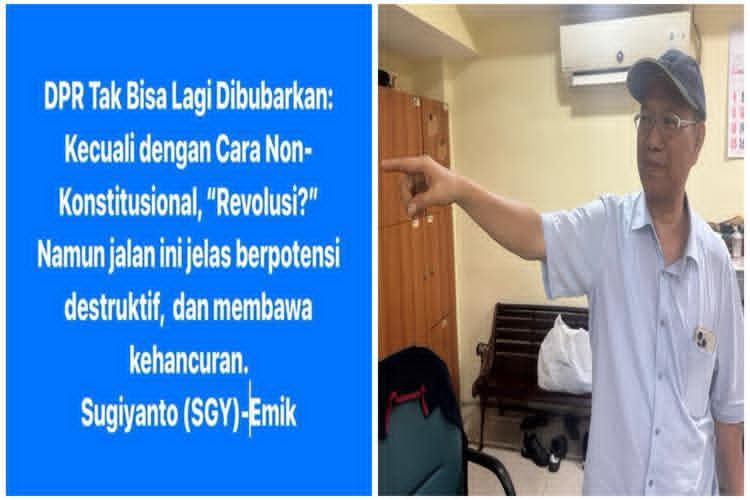
SECARA konstitusional, satu-satunya jalan untuk “menghapus” DPR adalah melalui amandemen UUD 1945
Oleh : Sugiyanto (SGY)
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)
Belakangan ini ramai dan viral di media sosial ajakan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Bahkan, beredar seruan demonstrasi pada 25 Agustus di depan Gedung DPR Senayan. Isu ini segera memicu polemik besar di tengah masyarakat.
Kritik terhadap DPR memang bukan hal baru. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, merespons isu tersebut dengan keras. Ia menyebut ajakan membubarkan DPR sebagai “mental orang tolol”. Pernyataan Sahroni memang tidak sepenuhnya benar dalam substansi politik, tetapi dari sudut pandang konstitusi ada dasarnya.
UUD 1945 hasil amandemen menutup celah pembubaran DPR oleh Presiden, sebagaimana tegas tertuang dalam Pasal 7C: Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Prinsip ini lahir dari sistem presidensial yang menempatkan eksekutif dan legislatif pada kedudukan sejajar untuk mencegah konsentrasi kekuasaan.
Meski begitu, politik selalu memiliki ruang kemungkinan. Istilah klasik, “politics is the art of the impossible, made possible,” tetap relevan.
Opini publik tentang “pembubaran DPR” mencuat mungkin karena kekecewaan yang meluas terhadap lembaga legislatif ini. Setelah saya telusuri, isu demonstrasi tersebut masih belum jelas penanggung jawabnya, sehingga besar kemungkinan hanya manuver politik. Namun demikian, tetap perlu diantisipasi segala kemungkinan, termasuk potensi aksi massa.
Kekecewaan masyarakat terhadap DPR mungkin muncul dari berbagai hal. Mulai dari gaji dan tunjangan besar yang sering disorot di media sosial, kebijakan kontroversial seperti revisi UU Pilkada yang dianggap mengakali putusan Mahkamah Konstitusi, hingga dugaan korupsi dan gaya hidup mewah anggota DPR. Publik juga menilai DPR kehilangan empati, seperti ketika anggota DPR berjoget riang dalam sidang sementara rakyat masih bergulat dengan kesulitan hidup.
Selain itu, ada ketidakpuasan terhadap produk legislasi yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, kesenjangan representasi di mana DPR dinilai tidak lagi benar-benar mewakili aspirasi publik, serta melemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Semua ini semestinya menjadi bahan introspeksi bagi seluruh anggota DPR, karena tugas utama mereka adalah menyuarakan kepentingan rakyat.
Sejarah mencatat, pembubaran DPR pernah terjadi. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno menerbitkan dekret untuk membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan menggantinya dengan DPR-GR serta MPRS. Tindakan itu jelas berada di luar kerangka konstitusi. Hal serupa terjadi pada 2001 ketika Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencoba membekukan DPR dan MPR lewat dekret. Namun, langkah itu segera dilawan melalui Sidang Istimewa MPR yang justru melengserkan Gus Dur.
Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa upaya membubarkan DPR secara ekstra-konstitusional selalu berujung pada krisis politik. Karena itu, pada era reformasi, melalui amandemen UUD 1945, posisi DPR diperkuat agar tidak bisa dibubarkan Presiden.
Secara konstitusional, satu-satunya jalan untuk “menghapus” DPR adalah melalui amandemen UUD 1945. Prosedur ini pun sangat sulit, karena perubahan konstitusi memerlukan persetujuan MPR yang sebagian besar anggotanya berasal dari DPR itu sendiri. Alternatif lain adalah melalui mekanisme Pemilu, yakni jika rakyat sama sekali tidak memilih wakilnya untuk duduk di DPR maupun DPRD. Namun, hal ini juga hampir mustahil terjadi. Dengan demikian, baik secara politik maupun praktis, upaya membubarkan DPR hampir tidak mungkin dilakukan.
Menyinggung istilah “kecuali revolusi?”, memang secara teori, revolusi atau kudeta bisa mengganti seluruh tatanan negara, termasuk membubarkan DPR. Namun jalan ini jelas berpotensi destruktif, menyalahi hukum, tidak memiliki legitimasi demokratis, dan berisiko besar menciptakan instabilitas politik serta kerusakan ekonomi.
Maka, jika ada ketidakpuasan terhadap DPR, solusinya bukan revolusi atau pembubaran paksa, melainkan reformasi yang terstruktur. Tekanan publik, advokasi politik, dan mendorong perubahan melalui mekanisme demokratis—termasuk amandemen konstitusi—adalah langkah yang lebih rasional, sah, dan sesuai dengan prinsip kenegaraan.
Kesimpulannya, DPR tidak dapat dibubarkan dalam kerangka sistem presidensial Indonesia. Jalan amandemen hampir mustahil ditempuh, sementara revolusi justru berpotensi membawa kehancuran.
Dalam konteks ini, saya menilai tidak akan terjadi revolusi hanya karena muncul opini yang meminta pembubaran DPR. Sebab, hingga saat ini belum terdapat kesalahan yang sagat fatal dari DPR yang benar-benar memicu kemarahan rakyat hingga mencapai klimaks.
Namun demikian, DPR perlu terus memperbaiki citra dengan bersikap lebih bijak: tidak mempertontonkan kemewahan di tengah penderitaan rakyat, tidak larut dalam euforia ketika rakyat menderita, dan tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
DPR harus kembali pada jati dirinya sebagai wakil rakyat sejati dengan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi kepentingan rakyat. Selain itu, DPR maupun DPRD perlu berani menggunakan hak konstitusionalnya—hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hanya dengan cara demikian, DPR dan DPRD dapat menjadi pilar demokrasi yang kuat sekaligus dipercaya masyarakat.